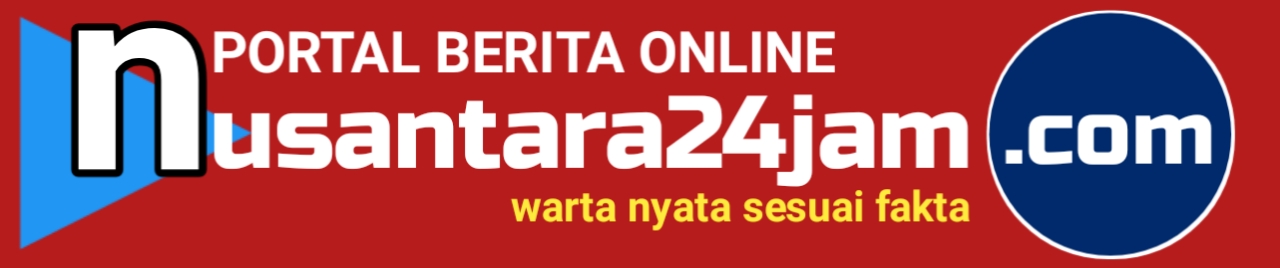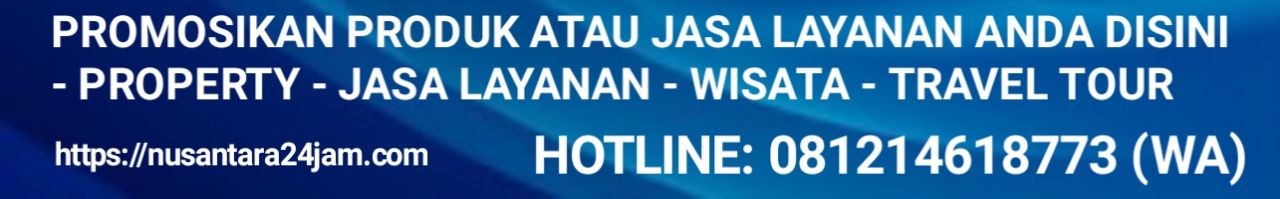

Oleh: Mastono S. Pd (Akdem 02)
N-24JAM – Sejak menapaki era Reformasi pada 1998, Indonesia telah mencatatkan berbagai capaian penting dalam perjalanannya sebagai negara demokrasi. Pemilihan umum secara langsung, kebebasan pers, penguatan partisipasi publik, serta munculnya berbagai lembaga pengawas independen menjadi fondasi penting dalam memperbaiki sistem politik yang sebelumnya dikekang oleh otoritarianisme. Meski demikian, perjalanan demokrasi Indonesia bukannya tanpa aral. Di balik kemajuan formal tersebut, tersembunyi berbagai tantangan mendasar yang mengancam kualitas demokrasi secara substansial.
Dalam refleksi ini, penting untuk melihat wajah politik Indonesia secara jujur: mengakui problem-problem yang ada, sekaligus tetap menjaga optimisme pada harapan dan peluang yang terbuka di masa depan.
Menguatnya Politik identitas
Salah satu tantangan utama yang belakangan kian menonjol adalah menguatnya politik identitas. Fenomena ini tampak dalam berbagai kontestasi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Politik identitas sering dimanfaatkan oleh sebagian elite politik untuk menggalang dukungan berbasis kesamaan suku, agama, ras, maupun golongan. Strategi semacam ini memang efektif dalam mengkonsolidasikan basis massa, namun dalam jangka panjang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.
Ketika politik identitas mendominasi, narasi kebangsaan yang inklusif perlahan-lahan tergerus. Polarisasi sosial menjadi konsekuensi logis. Masyarakat terbelah, bukan lagi berdasarkan adu gagasan atau program kerja, melainkan pada garis-garis primordial yang sempit. Politik menjadi ajang pertarungan “kami” versus “mereka”, bukan lagi kompetisi sehat berbasis visi kebangsaan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengikis sendi-sendi persatuan yang sejak awal menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia.
Korupsi menjadi problem klasik yang terus menghantui politik Indonesia. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, realitasnya kasus-kasus korupsi masih silih berganti terjadi. Ironisnya, sebagian besar pelaku justru berasal dari kalangan elite politik yang dipercaya rakyat.
Praktik politik transaksional sudah menjangkiti hampir seluruh lini proses demokrasi. Mulai dari perebutan kursi kekuasaan, pengadaan proyek pemerintah, hingga jual-beli jabatan di birokrasi. Tak jarang pula terjadi kompromi politik demi melanggengkan kekuasaan yang mengorbankan prinsip-prinsip etika publik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi negara dan elite politik kian merosot.
Lebih memprihatinkan lagi, dalam beberapa tahun terakhir KPK justru mengalami pelemahan. Perubahan regulasi dan intervensi kekuasaan membuat independensi lembaga antirasuah ini semakin dipertanyakan. Padahal, keberadaan lembaga yang kuat dan independen seperti KPK sangat krusial dalam menjaga marwah demokrasi yang bersih.
Fenomena oligarki menjadi salah satu ironi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Secara formal, Indonesia menganut sistem demokrasi multipartai. Namun dalam praktiknya, kekuatan modal dan jejaring elite tertentu sangat dominan dalam mengendalikan proses politik.
Oligarki politik-ekonomi ini menjelma dalam bentuk konglomerasi antara pebisnis, elite partai, dan pejabat publik. Mereka yang memiliki akses pada kekuasaan ekonomi cenderung memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan politik. Akibatnya, kebijakan publik lebih sering berpihak pada kepentingan segelintir kelompok, bukan kepentingan rakyat banyak.
Fenomena ini juga menghambat regenerasi politik yang sehat. Banyak politisi muda atau aktivis dengan rekam jejak bersih sulit menembus sistem yang sudah dikuasai oleh segelintir elite bermodal besar. Proses kandidasi dalam partai politik seringkali lebih ditentukan oleh kekuatan finansial, bukan oleh kapabilitas atau komitmen kebangsaan.
Penegakan hukum yang tidak independen menjadi tantangan krusial dalam menegakkan keadilan. Ketika institusi penegak hukum bisa diintervensi oleh kepentingan politik atau ekonomi, maka supremasi hukum menjadi ilusi belaka. Kasus-kasus besar yang melibatkan kekuasaan kerap “menguap” atau bahkan tidak pernah diproses secara serius.
Masyarakat semakin skeptis terhadap proses peradilan. Rasa ketidakadilan yang terus berulang memperbesar ketidakpercayaan pada sistem politik secara keseluruhan. Demokrasi tanpa supremasi hukum hanyalah prosedural belaka — tidak mampu menghadirkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Meski angka partisipasi pemilih dalam setiap pemilu cenderung tinggi, namun partisipasi substantif masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak pemilih masih terjebak dalam politik uang, kampanye hitam, dan informasi yang manipulatif. Dalam banyak kasus, pemilih cenderung memilih berdasarkan popularitas atau kedekatan identitas, bukan berdasarkan program dan rekam jejak calon.
Kondisi ini juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik masyarakat. Minimnya pendidikan politik yang bermutu membuat banyak warga negara tidak memiliki pemahaman yang kritis atas hak-hak politiknya. Akibatnya, demokrasi Indonesia lebih banyak berjalan secara prosedural, belum substantif.
Meski problematika yang dihadapi cukup kompleks, tetap ada alasan untuk optimis terhadap masa depan politik Indonesia. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran politik di kalangan generasi muda. Akses terhadap teknologi informasi membuat generasi milenial dan Gen Z lebih terbuka dalam menyuarakan aspirasi politiknya.
Media sosial menjadi ruang baru bagi anak muda untuk terlibat dalam diskursus politik, menyuarakan kritik, serta mengawasi kinerja pemerintah. Gerakan sosial berbasis isu-isu publik seperti lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, hingga transparansi anggaran mulai berkembang pesat. Fenomena ini menunjukkan adanya generasi baru yang tidak alergi terhadap politik, tapi justru ingin melakukan perubahan dari dalam.
Selain itu, beberapa partai politik mulai membuka diri terhadap regenerasi dan rekrutmen kader-kader muda profesional. Munculnya figur-figur pemimpin muda yang membawa gagasan segar menjadi oase di tengah stagnasi elite lama. Dengan dukungan masyarakat yang rasional, politik Indonesia perlahan bisa bertransformasi menuju arah yang lebih sehat.
Reformasi partai politik juga harus menjadi agenda penting ke depan. Tanpa pembenahan internal partai, sistem demokrasi kita akan terus dikuasai oleh patronase dan pragmatisme jangka pendek. Partai politik harus menjadi wadah kaderisasi yang sehat, bukan sekadar kendaraan politik bagi elite bermodal.
Tak kalah penting, penguatan lembaga-lembaga hukum harus terus diperjuangkan. Independensi KPK, penguatan Mahkamah Konstitusi, reformasi kejaksaan, dan profesionalisasi kepolisian merupakan pilar utama dalam membangun negara hukum yang kredibel.
Pada akhirnya, memperbaiki kualitas politik Indonesia bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau partai politik, melainkan menjadi proyek kolektif seluruh elemen bangsa. Masyarakat sipil, akademisi, media, komunitas profesional, hingga individu-individu biasa memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawal jalannya demokrasi.
Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna, namun ia memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, mengkritik, dan memperbaiki sistem. Dengan komitmen bersama, harapan akan hadirnya politik yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat bukanlah utopia belaka.
Masa depan politik Indonesia masih terbuka lebar. Pilihan ada di tangan kita: menjadi penonton yang pasif, atau menjadi aktor perubahan yang aktif.